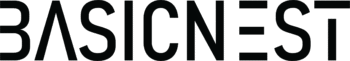Perjalanan saya ke Pangkajene Kepulauan dimulai dengan suara mesin kapal nelayan berukuran lebih dari 30 GT yang meraung menembus gelombang. Kapal ini sudah jauh berlayar sejak Pulau Sapeken, Madura, tempat saya menuntaskan sebuah penugasan. Tugas itu selesai, tetapi perjalanan belum usai. Haluan kapal diputar ke timur, mengarungi laut biru yang tak bertepi, menuju sebuah nama yang sebelumnya hanya singgah di telinga: Pulau Sailus, di pesisir Sulawesi Selatan.
Ketika pagi tiba, kapal perlahan mendekati tujuan. Sayangnya, pasang laut membuat kapal tak memungkinkan merapat ke dermaga kayu. Kami pun harus berpindah ke perahu kecil agar benar-benar bisa menjejak daratan. Dari kejauhan, garis pantai Sailus mulai tampak. Sinar matahari yang masih rendah memantul ke permukaan air, memberi kilau keemasan pada gelombang pasang.
Mesin kapal besar dimatikan, jangkar dijatuhkan, lalu saya berpindah ke perahu kayu bermesin tempel. Dari dek yang luas ke ruang sempit perahu kecil, saya merasakan pergeseran lain dari gemuruh mesin besar menuju dengung pelan, dari laut lepas menuju sebuah pulau kecil yang akhirnya bisa saya pijak.
Belajar Bertahan di Antara Pasang dan Sunyi
Begitu kaki saya menginjak Pulau Sailus, suasananya langsung terasa kontras dengan hiruk kota. Di sini, kehidupan berjalan dengan ritme yang sederhana, seakan diatur oleh keterbatasan yang sudah menjadi bagian keseharian. Pulau ini masuk dalam kategori pulau terluar, dan itu berarti warganya terbiasa hidup dengan listrik yang hanya menyala enam jam setiap malam.
Ketika langit gelap, bunyi mesin genset menggantikan sunyi. Suaranya monoton, tapi sekaligus menjadi tanda bahwa aktivitas malam dimulai. lampu-lampu rumah menyala, televisi berfungsi sebentar, dan anak-anak bisa belajar dengan cahaya lampu, meski hanya sebentar. Sementara itu, akses telekomunikasi pun berjalan seadanya. Satu-satunya provider yang hidup di sini adalah XL, dan itu pun sinyalnya sering kali hilang muncul.
Saya lalu teringat ucapan Pak Rasyid, seorang nelayan yang saya temui di beranda rumah panggungnya: “Akses di sini bukan soal jauh atau dekat. Tapi soal apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang ada.” Kalimat itu sederhana, tapi seakan merangkum realitas Sailus.
Pasar, misalnya, tak pernah ada. Untuk sayur-mayur, masyarakat hanya mengandalkan panen kecil di kebun sekitar atau pedagang keliling yang mendorong gerobak dari rumah ke rumah. Jika ingin daging, mereka harus memesannya dari Sumbawa, dengan waktu tunggu yang tidak pasti. Akhirnya, ikan—terutama ikan layang—menjadi penopang utama pangan sehari-hari. Dari laut, mereka mendapatkan sumber hidup, bukan hanya untuk makan, tetapi juga sebagai bagian dari identitas.
Mayoritas penduduk Sailus adalah etnis Mandar. Kehidupan mereka sehari-hari sepenuhnya berpaut pada laut. Kalender tak diukur dengan hari Senin atau Kamis, melainkan dengan arah angin, arus, dan cahaya bulan. Bagi mereka, laut bukan sekadar tempat bekerja. Ia adalah sahabat yang harus dipahami, guru yang harus dihormati, dan kitab yang terus dibaca ulang dari generasi ke generasi.
Senandung Nilai Bugis di Pulau Sailus
Saya mulai memahami bahwa kehidupan masyarakat kepulauan tak pernah lepas dari pandangan hidup yang diwariskan turun-temurun. Hampir setiap perbincangan dengan warga, entah di beranda rumah panggung atau di tepian pantai, selalu kembali pada keyakinan yang sama: laut adalah sumber hidup yang memberi sekaligus mengambil.
Suatu sore, matahari condong ke barat. Anak-anak berlarian sambil menendang bola plastik di pasir yang lembap, sementara suara debur ombak berpadu dengan tawa mereka. Di tepi pantai, seorang lelaki tua dari etnis Bugis duduk dengan tenang, tangannya sibuk memperbaiki jaring yang robek. Matanya sesekali menatap laut, seolah sedang membaca pesan yang dititipkan senja. Dari mulutnya, saya mendengar tiga kata yang menjadi kunci memahami cara mereka memaknai hidup: Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbi.
Sipakatau, jelasnya, adalah sikap saling menghargai dan memanusiakan sesama. Nilai ini terasa hidup dalam kebiasaan sederhana tetangga yang ringan hati berbagi ikan layang hasil tangkapan, atau seorang ibu yang menitipkan sebungkus sabal sebuah makanan lokal dari nasi dicampur kelapa parut sangrai kepada kerabat yang tidak sempat memasak. Bagi orang Sailus, solidaritas bukan sekadar pilihan, melainkan syarat untuk bertahan.
Falsafah berikutnya, Sipakainge, berarti saling mengingatkan. Seorang pemuda bercerita bahwa ayahnya selalu menasihati, “Kalau angin sudah miring, jangan nekat melaut.” Pesan sederhana itu bukan hanya soal keselamatan, tetapi juga tentang kesadaran bahwa hidup satu orang berkaitan erat dengan keberlangsungan keluarganya.
Saya juga sempat melihat seorang ibu menegur remaja yang hendak membuang sampah plastik ke laut. Dengan lembut ia berkata, “Nak, jangan buang di situ. Laut ini tempat kita cari makan.” Kalimat singkat itu menjadi pengingat nyata bagaimana menjaga alam berarti menjaga hidup bersama.
Terakhir, Sipakalebbi, yang bermakna menjaga martabat dan tidak merampas hak orang lain. Nilai ini tercermin dari harapan besar orang tua terhadap pendidikan anak-anak mereka. Meski akses sekolah terbatas, sekitar 30% anak muda Sailus berhasil kuliah dengan bantuan beasiswa banyak yang memilih jurusan kesehatan dan pendidikan.
“Kalau anak-anak bisa sekolah tinggi, kita tidak dipandang sebelah mata,” tutur seorang ibu dengan nada penuh kebanggaan. Ada keyakinan kolektif bahwa martabat masyarakat hanya bisa terjaga bila generasi muda berani menembus batas pulau.
Falsafah Bugis pada akhirnya bukan sekadar semboyan. Ia hidup dalam dapur-dapur yang memasak ikan layang, dalam kritik warga terhadap layanan kesehatan yang belum merata, hingga dalam semangat para orang tua menyekolahkan anaknya. Laut memang bisa memberi sekaligus mengambil, tetapi tiga falsafah itu membuat masyarakat tetap teguh menghadapi gelombang kehidupan.
Refleksi dari Pulau Sailus: Belajar dari Keterbatasan
Hidup di pulau kecil seperti Sailus memberi pelajaran yang sulit didapat dari ruang kelas atau seminar. Listrik yang hanya menyala enam jam setiap malam, pasar yang tak pernah ada, hingga pelayanan kesehatan yang serba terbatas, semua itu tidak membuat masyarakat berhenti melangkah. Justru dalam kekurangan, mereka menunjukkan kekuatan lain sebuah falsafah hidup yang diwariskan.
Tiga Falsafah nilai Bugis Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbi ternyata bukan sekadar ungkapan. Saya melihatnya hadir dalam dapur sederhana yang memasak sabal dari nasi dan kelapa sangrai, dalam solidaritas warga yang membagi ikan layang ketika tetangga tak sempat melaut, dalam nasihat orang tua agar anak-anak tak nekat melawan angin kencang di laut, hingga dalam tekad menyekolahkan generasi muda meski biaya dan jarak jadi tantangan.
Falsafah ini, bila ditarik lebih luas, bisa menjadi benteng menghadapi masalah sosial yang kerap muncul di banyak tempat intoleransi, persaingan tanpa empati, dan ketimpangan akses. Sailus mengingatkan bahwa nilai kebersamaan dan penghormatan pada sesama justru tumbuh kuat di wilayah yang dianggap terpinggirkan.
Perjalanan ini menegaskan, dokumentasi keindahan alam saja tak cukup. Menyusuri pulau terluar seperti Sailus berarti juga menelusuri nilai-nilai sosial yang bisa memberi jawaban sederhana untuk pertanyaan besar: bagaimana kita hidup bersama tanpa kehilangan rasa kemanusiaan.