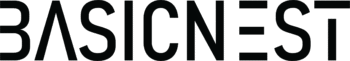“Jejak kosmos yang menyanyi dalam aksara Lontara”
Di tanah Sulawesi Selatan, di antara riuh laut dan senyap sawah, lahirlah sebuah epos yang begitu luas hingga dunia menyebutnya sebagai salah satu teks terpanjang yang pernah ditulis manusia. Namanya La Galigo. Dalam aksara Lontaraq, kisah ini menetes dari pena para pujangga Bugis selama berabad-abad, memanjang menjadi gulungan syair tak bertepi, seperti laut yang seakan tak berujung. Jika Mahabharata India atau Iliad Yunani menjadi mercusuar sastra dunia, maka La Galigo adalah samudra luas yang menyimpan pulau-pulau rahasia, belum banyak dikunjungi, bahkan oleh bangsa yang melahirkannya.
La Galigo tidak lahir dari sekadar imajinasi, melainkan dari pandangan kosmos. Bagaimana orang Bugis memahami langit, bumi, dan laut. Kisahnya bermula dari Batara Guru, putra langit yang diturunkan ke bumi untuk menata jagat dan melahirkan keturunan manusia. Dari sanalah garis nasab panjang terbentang, hingga muncul tokoh Sawerigading, sang pahlawan yang menyeberang lautan, mengarungi cinta, perang, dan perpisahan. Di setiap bait, laut bukan sekadar laut, melainkan takdir. Perahu bukan sekadar kayu yang mengapung, melainkan tubuh manusia yang berlayar di atas ombak kehidupan (Perdana 2019).
Ada getaran mitos, ada napas sejarah, ada percakapan abadi antara manusia dan kosmos. Membaca La Galigo adalah menyelam ke dalam cara pandang Bugis tentang dunia, bahwa alam bukanlah objek, melainkan saudara, bahwa kehormatan (siri’) adalah inti dari kemanusiaan, bahwa hidup harus dijaga dalam keseimbangan.
Namun ironisnya, samudra sebesar itu justru jarang terdengar di layar kaca, jarang menempati ruang publik kita yang sering kali lebih sibuk merayakan mitos asing ketimbang khazanah sendiri.
Sawerigading Pelayar Jiwa di Laut Takdir
Di pusat cerita La Galigo, berdiri gagah tokoh Sawerigading. Ia adalah anak dari Batara Lattu dan We Nyiliq Timoq. Sosoknya setengah mitos, setengah manusia. Kepadanya dilekatkan segala hasrat yang paling purba. Cinta yang melampaui batas, kerinduan yang menyeberang pulau, dan perang yang menguji harga diri.
Sawerigading jatuh cinta pada We Cudai, perempuan yang tak lain adalah kembarannya sendiri. Cinta itu mustahil, dilarang oleh kosmos, dan akhirnya dipisahkan. Namun justru di situlah epos ini menyalakan api. Cinta yang terlarang memaksa sang pahlawan mengembara. Ia berlayar ke negeri-negeri jauh, menaklukkan samudra, menemukan pulau baru, dan menulis takdir baru bagi keturunannya.
Kisahnya ibarat cermin dari jiwa Bugis sendiri, bangsa pelaut yang berani menyeberang samudra, mencari tanah baru, dan menjalin perniagaan lintas benua. Sawerigading bukan hanya tokoh mitos, melainkan arketipe dari manusia Bugis. Keras kepala namun penuh cinta, tangguh dalam badai namun rapuh di hadapan kerinduan.
Ketika kita membaca bait-bait panjang La Galigo, kita seolah mendengar ombak memanggil nama kita sendiri. Sawerigading berbicara kepada setiap manusia yang pernah merasakan rindu tak terjawab, yang pernah meninggalkan rumah demi takdir, yang pernah berlayar tanpa tahu pantai mana yang akan menyambut. Di sinilah La Galigo menjelma universal. Ia bukan sekadar milik Bugis, tapi milik siapa saja yang pernah hidup dengan jantung berdebar, yang pernah mencari arti dalam perjalanan panjang kehidupan (Pongsibanne, Ag, dan Si t.t.).
Legenda yang Jarang Terekspos
Dalam riuh dunia modern, di mana layar kaca lebih sering menampilkan mitos superhero dari barat, La Galigo nyaris tidak terdengar. Padahal, UNESCO telah mengakui naskah ini sebagai Memory of the World sejak 2011. Ironis, kita lebih hafal kisah Thor sang dewa petir daripada Sawerigading yang berlayar di samudra kita sendiri.
Inilah alasan mengapa La Galigo begitu penting untuk diangkat kembali. Bukan sekadar sebagai warisan budaya, tapi sebagai “cerita membanggakan” yang menunggu diceritakan ulang di panggung dunia. Dalam bait-baitnya tersimpan nilai tentang kesetiaan, keseimbangan, kehormatan, dan hubungan mesra antara manusia dengan alam. Nilai-nilai itu relevan di tengah krisis ekologi dan krisis moral hari ini.
La Galigo mengajarkan kita bahwa dunia adalah jaringan kosmos: manusia, laut, tanah, dan langit terhubung. Jika satu simpul rusak, keseimbangan hancur. Bukankah itu juga yang kita saksikan hari ini ketika hutan digunduli, laut tercemar, dan manusia terasing dari akarnya?
Membawa La Galigo ke ruang publik adalah mengembalikan kebanggaan yang lama terkubur. Ia adalah kisah yang bisa membuat generasi muda Indonesia menegakkan kepala, menyadari bahwa nenek moyang mereka bukan hanya pelaut tangguh, tetapi juga penyair agung.
Mungkin memang La Galigo tidak mudah, panjang, rumit, penuh metafora. Namun justru di situlah letak keindahannya. Seperti samudra, ia tidak bisa diteguk sekaligus, tapi mesti diselami perlahan, dengan kesabaran dan hormat.
Mungkin suatu hari nanti, La Galigo akan diadaptasi menjadi teater agung, film epik, atau karya sastra modern yang menyentuh dunia. Namun sebelum semua itu, kita sendiri sebagai anak negeri, harus berani menengoknya kembali, menyebut namanya, dan menghidupkannya dalam percakapan kita sehari-hari. Karena La Galigo bukan sekadar kisah kuno, melainkan jati diri yang sedang menunggu untuk dikenali kembali.
Menyulam Samudra dalam Ingatan
La Galigo adalah samudra yang ditulis dengan aksara, sebuah nyanyian panjang yang lahir dari tanah Bugis, namun gema suaranya seharusnya sampai ke seluruh dunia. Dalam bait-baitnya, kita menemukan asal-usul manusia, rahasia laut, dan kerinduan yang tak pernah padam.
Sawerigading mengajarkan bahwa hidup adalah pelayaran, kadang melawan ombak, kadang mencari pantai baru, tapi selalu menuju takdir yang lebih luas. La Galigo sendiri adalah perahu raksasa dan mengajak kita naik ke dalamnya, menyeberangi masa lalu menuju masa depan (Sua, Asfar, dan Adiansyah 2023).
Dan di tengah dunia yang kerap melupakan akar sendiri, La Galigo berdiri sebagai “legenda membanggakan” yang jarang terekspos. Ia menunggu kita untuk membacakannya kembali, bukan sekadar sebagai teks, melainkan sebagai napas kebudayaan.
Mungkin di situlah tugas kita untuk menjaga agar samudra ini tidak mengering, agar puisi kosmos ini tidak sunyi, agar La Galigo tetap hidup sebagai bukti bahwa Indonesia tidak pernah kehabisan kisah agung, hanya perlu keberanian untuk mengangkatnya ke cahaya.
REFRENSI
Perdana, Andini. 2019. “NASKAH LA GALIGO: IDENTITAS BUDAYA SULAWESI SELATAN DI MUSEUM LA GALIGO.” 5(1).
Pongsibanne, Lebba, S. Ag, dan M. Si. t.t. “Lebba Pongsibanne, M.Si, dkk.”
Sua, Andi Tenri, Andi Muhammad Irfan Taufan Asfar, dan Romi Adiansyah. 2023. “Penguatan Pemahaman Budaya Indonesia pada SB Hulu Langat Melalui Metode Discovery Learning Cerita Rakyat ‘I La Galigo.’” Buletin KKN Pendidikan 5(1):27–36. doi:10.23917/bkkndik.v5i1.22486.