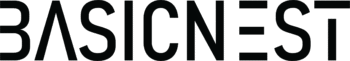Nashrul mu’minin Content Writer Yogyakarta
Revolusi teknologi yang melaju begitu pesat di abad ke-21, khususnya dengan hadirnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), telah membawa perubahan besar dalam hampir seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali pendidikan. Di tahun 2025, kita tidak lagi sekadar bicara soal pemanfaatan internet atau pembelajaran daring sebagai inovasi. Kita tengah menyaksikan transisi masif menuju sistem pembelajaran yang dikendalikan oleh algoritma, data besar (big data), serta kecerdasan mesin yang mampu meniru dan bahkan mengungguli beberapa kemampuan manusia, termasuk dalam proses mengajar dan belajar.
AI telah memasuki ruang kelas, menggantikan sebagian peran guru sebagai penyampai materi. Platform-platform pembelajaran berbasis AI kini dapat menyesuaikan konten sesuai dengan gaya belajar, tingkat pemahaman, dan minat masing-masing peserta didik. AI tak hanya menyampaikan pelajaran, tetapi juga mampu memberikan evaluasi instan, menganalisis kelemahan siswa, hingga menyarankan metode belajar yang lebih efektif. Di satu sisi, ini merupakan terobosan besar dalam mempercepat proses pendidikan. Namun di sisi lain, ini memunculkan pertanyaan serius: Apakah seluruh peserta didik dan tenaga pengajar siap menghadapi perubahan ini? Dan jika tidak, siapa yang akan tertinggal?
Masalah kesiapan dalam menghadapi era AI ini bukan hanya persoalan memiliki akses terhadap teknologi. Lebih dari itu, ini adalah soal literasi digital, kemampuan berpikir kritis, adaptasi terhadap perubahan, dan keberanian keluar dari zona nyaman. Tidak sedikit siswa dan guru yang merasa tertinggal karena belum terbiasa menggunakan teknologi yang kompleks. Bahkan, banyak institusi pendidikan yang masih terpaku pada metode pembelajaran tradisional dan belum mampu memanfaatkan potensi AI secara optimal. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tantangan ini makin berat karena masih banyak wilayah yang belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai. Akibatnya, ketimpangan pendidikan berbasis teknologi semakin nyata.
Fenomena “siapa siap, siapa tersisih” bukan hanya terjadi di antara siswa, tetapi juga guru. Profesi guru kini menghadapi tantangan eksistensial. Guru yang tidak mengikuti perkembangan teknologi, enggan belajar, atau bersikap defensif terhadap AI berisiko kehilangan relevansi. Sementara itu, guru-guru yang mampu memanfaatkan teknologi untuk memperkuat perannya—sebagai fasilitator, mentor, dan pembentuk karakter—justru akan semakin dibutuhkan. Artinya, AI bukan untuk menggantikan guru, melainkan untuk memperkuat dan mempermudah proses pembelajaran, selama guru itu sendiri mau berubah dan belajar ulang.
AI juga menantang konsep kurikulum konvensional. Di era AI, materi yang diajarkan tidak lagi cukup hanya mengandalkan hafalan atau kompetensi teknis dasar. Kurikulum masa depan harus menekankan pada soft skills, pemecahan masalah, kerja tim, kreativitas, dan etika. Anak-anak perlu dipersiapkan bukan hanya untuk menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta dan pengkritiknya. Oleh karena itu, pembelajaran harus diarahkan untuk membentuk manusia yang adaptif, berempati, dan punya kapasitas berpikir lintas bidang—kemampuan yang justru tidak dimiliki oleh AI.
Namun demikian, transisi menuju sistem pendidikan yang berbasis AI bukan tanpa risiko. Salah satunya adalah potensi kehilangan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses pembelajaran. AI tidak memiliki empati, tidak bisa menenangkan siswa yang cemas, atau memahami konteks budaya dan sosial secara mendalam. Inilah mengapa peran guru tetap penting, terutama dalam membangun relasi sosial dan menanamkan nilai-nilai moral serta kebangsaan. Oleh sebab itu, pendidikan di era AI perlu dijalankan secara seimbang: antara teknologi dan sentuhan manusia.
Persoalan etika juga menjadi penting dalam penggunaan AI di dunia pendidikan. Siapa yang mengontrol data siswa? Apakah AI akan memperkuat bias-bias yang ada dalam sistem? Bagaimana kita memastikan bahwa teknologi ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan komersial semata, tetapi benar-benar untuk memperbaiki kualitas pendidikan? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab secara kritis oleh para pembuat kebijakan, pendidik, dan masyarakat.
Tidak hanya itu, masuknya AI ke dalam sistem pendidikan juga akan membentuk kembali pasar tenaga kerja masa depan. Kompetensi yang dibutuhkan akan sangat berbeda dengan saat ini. Banyak pekerjaan lama akan tergantikan oleh mesin, sementara pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya akan bermunculan. Maka dari itu, sistem pendidikan harus mulai mempersiapkan generasi muda untuk memasuki dunia yang sangat dinamis dan tidak pasti. Pendidikan tidak bisa lagi fokus pada satu jalur profesi atau keterampilan tetap, melainkan harus mampu membekali peserta didik dengan daya lenting (resilience) dan kemauan belajar sepanjang hayat (lifelong learning).
Bahkan, peran keluarga sebagai pendidik pertama pun harus diperkuat. Dalam situasi ketika anak belajar dari rumah menggunakan AI, orang tua harus memiliki kesadaran dan keterampilan dasar untuk mendampingi anak, bukan hanya menyerahkan sepenuhnya kepada teknologi. Di sinilah pentingnya edukasi publik tentang AI, agar tidak menciptakan generasi yang canggih secara teknologi namun miskin karakter dan nilai.
Menurut saya, kehadiran AI dalam pendidikan adalah peluang sekaligus ujian. Siapa yang siap beradaptasi, memperkuat literasi digital, dan terus belajar, akan menjadi bagian dari gelombang kemajuan. Sebaliknya, mereka yang menolak berubah, berpegang pada cara lama, atau tidak mendapatkan akses yang adil, akan tertinggal jauh. Pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan siswa harus bekerja sama memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk memperkuat sistem, bukan memperlebar jurang ketimpangan.
Belajar di era AI bukan lagi soal apakah kita akan menggunakan teknologi atau tidak, melainkan bagaimana kita menggunakannya secara bijak dan inklusif. Pendidikan 2025 menuntut kesiapan bukan hanya dari segi fasilitas, tetapi juga dari mentalitas. Jika kita tidak segera berbenah dan menyusun strategi yang tepat, maka sistem pendidikan kita bukan hanya akan tersisih, tetapi juga gagal membekali generasi penerus bangsa untuk menghadapi masa depan yang serba tidak pasti.