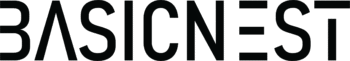Bayangkan sebuah kata diucapkan untuk terakhir kalinya di muka bumi. Bukan sekadar kata, melainkan sebuah kunci menuju semesta pemikiran yang unik. Sebuah kata yang pernah menamai jenis angin yang hanya berembus di sore hari, memanggil kekasih dengan nada yang tak bisa ditiru bahasa lain, atau merapalkan doa kepada leluhur yang namanya kini terlupakan. Bayangkan kata itu, setelah diucapkan, lenyap ditelan sunyi. Ia tidak terekam dalam arsip digital, tidak tertulis di atas daun lontar, dan tidak akan pernah lagi bergetar di pita suara manusia. Ini bukanlah adegan pembuka dari sebuah film fiksi ilmiah tentang kiamat, melainkan sebuah tragedi senyap yang telah terjadi, berulang kali, di tanah kita sendiri. Salah satu babak terakhirnya berlangsung di Pulau Buru, Maluku. Di sanalah gema penghabisan dari bahasa Hukumina memudar, meninggalkan kekosongan budaya yang tak akan pernah bisa terisi kembali.
Kisah Hukumina adalah sebuah elegi, sebuah nyanyian duka untuk kehilangan yang begitu mendalam, yang sering kali tak terlihat dan tak terdengar di tengah riuh rendahnya modernitas. Ini adalah “cerita membanggakan yang tak terlihat di layar kaca” dalam wujudnya yang paling murni dan paling tragis. Pahlawannya bukanlah jenderal atau atlet, melainkan para penutur terakhir yang suaranya kini telah diam. Warisannya bukanlah monumen megah, melainkan sebuah dunia yang terkubur bersama mereka, sebuah cara pandang yang kini hilang selamanya dari perbendaharaan kolektif umat manusia.
Indonesia, negara kepulauan yang kita banggakan, adalah sebuah anomali linguistik, sebuah keajaiban keragaman bahasa. Menurut data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga tahun 2019, Indonesia tercatat memiliki 718 bahasa daerah. Angka ini menempatkan kita di urutan kedua di dunia setelah Papua Nugini, sebuah fakta yang seharusnya menjadi sumber kebanggaan nasional yang tak terhingga. Namun, di balik kemegahan statistik tersebut, tersembunyi sebuah krisis yang berjalan dalam senyap. Sebagian besar dari ratusan bahasa ini, terutama yang berada di wilayah timur Indonesia, kini berada di ambang kepunahan. Maluku, yang dijuluki “Kepulauan Rempah-Rempah” karena kekayaan alamnya, juga merupakan sebuah laboratorium linguistik raksasa. Namun, di sini pula banyak bahasa yang menemui ajalnya.
Mengutip data yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga, termasuk UNESCO, bahasa Hukumina secara resmi dinyatakan punah. Ia tidak sendirian. Di pemakaman linguistik Maluku, Hukumina berbaring di samping nama-nama lain yang kini hanya menjadi catatan kaki sejarah: Kayeli, Palumata, Piru, Moksela, Nila, dan beberapa lainnya. Masing-masing nama mewakili sebuah semesta kebudayaan yang telah lenyap. Dalam sebuah tulisan reflektif yang terbit di jurnal Patrawidya, para peneliti yang bekerja di Maluku Barat Daya mengajukan pertanyaan yang menusuk kalbu: “Bagaimana jika suatu saat bahasa itu lenyap tertanam di dalam tanah bersama tubuh mereka? Apakah layak untuk disesali?”. Pertanyaan ini bukanlah sekadar retorika akademis. Ia adalah sebuah jeritan dari garis depan perjuangan pelestarian budaya, sebuah pengingat bahwa yang hilang bukanlah sekadar kumpulan kata, melainkan jiwa dari sebuah komunitas.
Untuk memahami skala tragedi ini, kita harus terlebih dahulu memahami apa itu bahasa. Bahasa bukanlah sekadar alat komunikasi. Ia adalah sebuah arsip raksasa dari kearifan turun-temurun, sebuah lensa unik untuk memandang dunia. Setiap bahasa memiliki caranya sendiri dalam mengkategorikan realitas, mengungkapkan emosi, dan menceritakan asal-usul. Di dalam sebuah bahasa terkandung pengetahuan intim tentang ekologi lokal, navigasi bintang, khasiat tanaman obat, silsilah keluarga yang rumit, dan konsep-konsep spiritual yang tak dapat diterjemahkan dengan sempurna ke dalam bahasa lain. Ketika bahasa Hukumina punah, kita tidak akan pernah tahu kata apa yang mereka gunakan untuk membedakan lima jenis hujan yang turun di musim pancaroba, atau bagaimana mereka menamai puluhan jenis ikan di teluk sekitar mereka dengan presisi yang melampaui taksonomi Linnaeus.
Kita kehilangan cara pandang mereka tentang hubungan antara manusia, alam, dan leluhur. Kepunahan sebuah bahasa setara dengan terbakarnya sebuah perpustakaan Aleksandria yang seluruh koleksinya belum pernah dibaca oleh dunia luar. Ini adalah kehilangan permanen bagi warisan intelektual seluruh umat manusia. Kebanggaan yang terkandung dalam cerita ini bukanlah kebanggaan atas kejayaan masa lalu yang gemilang, melainkan kebanggaan atas kekayaan pemikiran dan cara hidup yang pernah ada. Membanggakan bahwa di sudut kecil dunia, di Pulau Buru, pernah hidup sekelompok manusia dengan cara pandang yang begitu unik, yang terekam dalam getaran pita suara mereka. Menghargai keberadaan mereka, meskipun kini hanya dalam kenangan, adalah bentuk penghormatan tertinggi.
Kita mungkin tidak akan pernah tahu siapa nama penutur terakhir bahasa Hukumina. Tidak ada kamera yang merekamnya, tidak ada wartawan yang mewawancarainya. Namun, kita bisa membayangkan sosoknya berdasarkan kisah-kisah serupa dari para peneliti yang berpacu dengan waktu di pelosok-pelosok Maluku. Bayangkan seorang lelaki tua, usianya mungkin sudah lebih dari 70 tahun, duduk di beranda rumah panggungnya, menatap laut yang telah memberinya kehidupan. Ingatannya adalah kamus hidup terakhir dari bahasanya. Para peneliti yang pernah mendokumentasikan bahasa-bahasa terancam punah di Maluku Barat Daya menceritakan pertemuan mereka dengan orang-orang bijaksana seperti dia tokoh adat seperti Joksan Romer atau Ruland Surlialy, keduanya berusia 77 tahun saat ditemui. Mereka adalah para pemegang kunci terakhir dari sebuah dunia yang sekarat.
Ketika mereka berbicara dalam “bahasa tanah” mereka, kata-kata yang keluar adalah artefak hidup, gema dari masa lalu yang masih bergetar di udara. Namun, gema itu semakin lemah. Proses peralihan bahasa, seperti yang dijelaskan dalam berbagai kajian vitalitas bahasa, terjadi secara perlahan namun pasti. Generasi anak-anak dan cucu mereka, karena tuntutan pendidikan formal yang menggunakan bahasa Indonesia, perkawinan campur dengan suku lain, dan dominasi bahasa Melayu Ambon sebagai lingua franca, tidak lagi mewarisi bahasa ibu mereka. Transmisi antargenerasi proses fundamental pewarisan bahasa dari orang tua kepada anak di dalam keluarga terputus. Ketika proses ini berhenti, sebuah bahasa memasuki fase terminal. Penuturnya yang tersisa hanyalah kaum lansia, dan ketika mereka berpulang, bahasa itu pun ikut terkubur bersama mereka.
Lantas, apakah kita hanya bisa meratapi kehilangan ini? Tentu tidak. Kisah kepunahan Hukumina harus menjadi cambuk, bukan hanya nisan untuk ditangisi. Di tengah ancaman kepunahan massal ini, ada secercah harapan yang dinyalakan oleh para pejuang bahasa. Lembaga-lembaga seperti Kantor Bahasa Provinsi Maluku dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus berupaya melakukan pendokumentasian dan revitalisasi. Upaya ini, seperti yang digambarkan dengan puitis dalam sebuah artikel, adalah sebuah “jalan sunyi di atas ombak”, sebuah perjuangan berat yang membutuhkan komitmen luar biasa di tengah lautan tantangan. Pendokumentasian adalah langkah pertolongan pertama, sebuah tindakan penyelamatan darurat. Para peneliti dan pegiat budaya merekam kosakata, cerita lisan, dan dialog sehari-hari untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari bahasa-bahasa yang terancam punah.
Ini adalah upaya untuk membangun sebuah bahtera digital, mengarsipkan kearifan sebuah budaya sebelum banjir kepunahan menenggelamkannya sepenuhnya. Langkah selanjutnya adalah revitalisasi, atau menghidupkan kembali. Ini adalah tugas yang jauh lebih sulit dan kompleks. Upaya ini bisa berupa memasukkan bahasa daerah ke dalam kurikulum sekolah, mengadakan lomba dan kompetisi, atau mendorong penggunaannya kembali di lingkungan keluarga dan upacara adat. Pemerintah Provinsi Maluku, menurut sebuah penelitian, sebenarnya mendukung kebijakan pemertahanan bahasa daerah, namun upaya ini seringkali belum cukup untuk meningkatkan vitalitas bahasa secara signifikan di tengah gempuran zaman. Revitalisasi membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan; ia membutuhkan kebanggaan dan kemauan dari komunitas penutur itu sendiri untuk merebut kembali warisan mereka.
Kisah Hukumina adalah cermin bagi ratusan bahasa daerah lain di Indonesia yang kini berada di jalur yang sama. Ia mengajarkan kita sebuah pelajaran penting: keragaman budaya adalah ekosistem yang rapuh. Ia membutuhkan perawatan, penghormatan, dan perlindungan aktif dari kita semua. Kehilangan satu bahasa adalah kehilangan bagi kita semua, karena itu berarti menyempitnya cakrawala kemungkinan cara menjadi manusia. Gema terakhir dari tanah Hukumina mungkin telah lenyap, tetapi semangatnya tidak boleh padam. Ia harus terus bergema di ruang-ruang diskusi, di kebijakan pemerintah, dan yang terpenting, di dalam kesadaran kita. Sudah saatnya kita melihat bahasa daerah bukan sebagai peninggalan masa lalu yang usang dan tidak relevan, melainkan sebagai pusaka hidup yang menyimpan kearifan untuk masa depan. Mari kita dengarkan baik-baik suara-suara yang masih tersisa di pelosok negeri ini. Mari kita hargai setiap dialek, setiap logat, setiap kata unik yang diucapkan oleh para tetua kita. Karena di dalam setiap kata itu, tersimpan sebuah cerita membanggakan yang tak akan pernah bisa diciptakan ulang. Jangan sampai kita baru menyadari betapa berharganya suara mereka ketika yang tersisa hanyalah keheningan abadi.