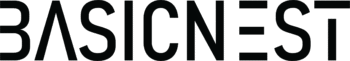Di Tatar Sunda, gunung bukan sekadar gundukan tanah yang menyusun rimba raya dan menadah air hujan. Gunung dipandang sebagai sumbu dunia, menyatukan bumi tempat manusia berpijak dan langit sebagai kayangan. Gunung-gunung menjulang sejak ratusan tahun. Berdiri memberi kehidupan pada kampung-kampung yang merentang di kakinya, persis seperti nasi tumpeng.
Tidak terkecuali Gunung Gede yang menjadi pasak bagi kawasan penyangganya seperti Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Siapa yang tidak bangga dengannya? Gunung dengan tinggi 2.958 meter di atas permukaan laut (mdpl) ini telah menjadi rumah bagi berbagai satwa dan tumbuhan. Mulai dari owa dan elang jawa, hingga rasamala dan edelweiss.
Bahkan Gunung Gede adalah tempat yang hidup dan menjadi hunian bagi para makhluk halus dan leluhur. Keyakinan lokal tentang penunggu tak kasat mata ini datang dari salah satu bukit yang berada di kakinya. Namanya Pasir Sarongge, yang menurut naskah Sanghyang Siksakanda ng Karesian (1518 Masehi) berarti tempat angker yang dihuni kekuatan jahat.
Menapaki waktu yang panjang sebagimana kawasan lain yang disokong kesuburan Gunung Gede, Pasir Sarongge tumbuh menjadi ruang hidup bagi masyarakat Cianjur yang tinggal di bagian utara. Di tempat ini, penghormatan terhadap Eyang Suryakancana hadir melalui tuum peda (sejenis tim ikan asin) pada setiap waktu tertentu seperti bulan mulud atau menjelang perayaan kenaikan kelas di sekolah dasar. Peda yang sejatinya merupakan ikan kembung, makerel, atau sejenisnya yang lalu mengalami penggaraman dan fermentasi, berubah menjadi alat komunikasi lintas dimensi. Makanan ini menjadi penjaga ingatan bahwa manusia tidak pernah tinggal sendirian.
Melalui aroma khasnya yang menyengat, ia membawa pesan tentang relasi kosmik di antara manusia, roh penunggu, dan gunung. Tuum peda tidak hanya menguatkan solidaritas warga Sarongge dalam acara makan bersama, juga keluarga-keluarga batih yang menyajikannya direkatkan dalam jalinan yang harmonis. Dalam kepulan asap kemenyan yang mengepul dan tawasul yang terapal, doa membubung menyatukan manusia yang penuh rasa syukur dengan kehadirat Ilahi melalui syafaat Nabi, jalan para wali, petuah tetua-tetua kampung, dan arwah orang tua yang sudah bersemayam di keabadian.
Melampaui ruang dan zaman, kumpulan orang-orang yang sedang selamatan seakan mengundang seluruh makhluk hidup untuk sekali lagi tunduk pada kehendak Tuhan yang menjelma melalui kaidah alam. Berharap wortel yang dipanen juga tekukur yang diburu, cukup menunjang hajat hidup warga sehari-hari. Dengan harganya yang terjangkau, peda sang lauk murah itu tampil menjadi simbol kerakyatan yang bersahaja, ketulusan resiprokal dalam mencintai gunung. Sajian ini juga merepresentasikan keseimbangan semesta khas Nusantara, laut sebagai asalnya dan gunung sebagai tempat dipersembahkannya.
Seperti orang Sunda pada umumnya, orang-orang di Pasir Sarongge percaya bahwa senja hari merupakan waktu yang sakral. Titik transisi yang menggulirkan siang ke malam ini disebut dengan sandékala, membuka tirai pembatas antara dunia manusia dengan bangsa lelembut. Tipis dan sensitif. Orang-orang terdahulu memberi kesaksian tentang hilangnya warga akibat keluyuran tak tahu waktu, katanya diculik kélong wéwé. Bahkan beberapa warga yang pernah mengalami mati suri menuturkan pengalamannya bekerja di kerajaan. Peradaban ini terletak di alun-alun yang membentang di puncak Gunung. Buah tomat sebesar bedug dan cabai seukuran kentungan.
Kehidupan di Pasir Sarongge menggeliat, renovasi rumah minimalis, mobil kekinian, termasuk akses internet yang turut masuk. Memang tidak sekuat masyarakat adat yang menyandarkan diri pada tradisi leluhur, tapi Sarongge juga membuahkan gagasan genius tentang kerud. Ia adalah makhluk setengah macan atau kera dengan gumpalan rambut yang menutupi matanya. Adapun juga warga yang bilang, kerud merupakan anjing yang kepalang tua lalu berubah menjadi siluman. Orang-orang Sarongge percaya makhluk ini memiliki kuku yang panjang, sekali tebas dapat membunuh mangsanya. Suaranya pun khas, jika terdengar samar dan jauh artinya kerud sedang mendekat. Begitupun sebaliknya saat suaranya terdengar jelas seperti dekat, justru manusia sedang berada dalam zona yang aman.
Terlepas dari spekulasinya yang mungkin ditertawakan sebagai pikiran primitif ala orang kampung, mitos mempunyai posisinya sendiri. Dalam masyarakat pegunungan, ia beroperasi meneratas nalar kecerdasan lokal. Sandékala yang secara harfiah berarti ‘saat rahasia’ berhasil memagari perilaku manusia untuk lebih tahu diri tak berlebihan. Dengan demikian orang-orang Sarongge menempatkan tubuhnya dengan etis untuk berhenti beraktivitas, rehat sejenak dari hasrat berkelana di dalam alam. Pengaturan waktu lokal yang muncul dalam pantangan, mendidik publik untuk memandang alam dengan cara pandang yang wajar. Orang-orang yang serakah tak kenal waktu justru dicap kamalinaan, keterlaluan.
Begitu juga kerud telah menjaga Gunung Gede dari potensi kehancuran akibat keserakahan manusia yang tergoda menambang pasir di area tebing curamnya. Nyatanya lereng-lereng dan puncak cukup lestari, menyediakan gua bagi landak juga bagi manusia dengan udara segar, kesuburan, dan air yang bersih. Bayangkan jika sepenuhnya religi lokal ini raib, bagaimana dengan nasib Gunung Gede termasuk kehidupan yang berlangsung di dalamnya? Bisakah sepenuhnya mengandalkan sains modern?
Meskipun perlahan telah banyak pergeseran di situasi kontemporer ini baik dalam kepercayaan maupun praktiknya, namun mitos tetap layak dipertimbangkan untuk dihidup-hidupi dalam etos yang baru dengan nafas konservasi alam yang tidak boleh berubah. Hal-hal yang tampak mistik bukan omong kosong liar yang hanya berguna untuk menakut-nakuti anak-anak. Semuanya adalah bentuk kekayaan intelektual dan identitas lokal. Kala kebudayaan di suatu tempat bergelanggang, sistem religi setempat turut melembaga menjadi memori kolektif warga. Hantu dan dunianya dalam beradab-abad yang lalu telah tampil menjadi penanda batas yang menumbuhkan etika ekologis, termasuk di tengah kehidupan orang-orang Sarongge.