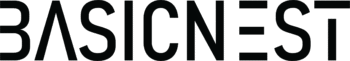Asap knalpot masih menggantung di udara ketika suara kenong dan kendang tiba-tiba menggulung suasana jalan Desa Jojogan. Para pengendara menoleh, seolah waktu mendadak melambat bahkan berhenti menginjak standar motor. Warga berbondong-bondong merapat ke sisi jalan, sebagian membawa kursi plastik, sebagian lagi berdiri sambil menenteng anak kecil. Sebuah panggung sederhana terbentuk, bukan di lapangan terbuka seperti dulu, melainkan di ruas jalan yang sengaja ditutup sementara. Dari kejauhan, bunyi gamelan mulai terdengar: kendang yang memukul irama cepat, gong yang bergetar dalam, dan suara sinden yang melengking, menandai bahwa pertunjukan ebeg akan segera dimulai.
Ebeg atau sering disebut kuda lumping, bukan sekadar hiburan rakyat. Ia adalah denyut nadi yang terus berdetak di tengah masyarakat Desa Jojogan, Kabupaten Pemalang. Tidak ada catatan pasti sejak kapan ebeg hadir, tetapi hampir setiap orang di sini percaya bahwa kesenian ini merupakan warisan tradisi Jawa kuno, yang merepresentasikan semangat prajurit berkuda dalam peperangan.
Bagi masyarakat Pemalang, ebeg bukan hanya tontonan, melainkan juga ruang perjumpaan. tempat orang saling menyapa, berbincang, dan merayakan kebersamaan.
Alunan Sinden.
Di tengah dentuman musik tradisional jawa, suara lembut seorang sinden muncul, merdu sekaligus kuat. Namanya Mbak Sum, perempuan paruh baya yang sudah bertahun-tahun setia mengiringi ebeg dengan suaranya. Rambutnya disanggul sederhana, kebaya cokelat tua melekat di tubuhnya, wajahnya tenang meski peluh menetes perlahan.
“Kalau orang dengar suara sinden, mereka langsung tahu bahwa ebeg sudah dimulai. Tugas saya bukan hanya menyanyi, tapi juga memberi nyawa pada pertunjukan” ujarnya sambil tersenyum ketika ditemui usai pentas.
Bagi Mbak Sum, menyinden bukan sekadar pekerjaan, melainkan sebuah hobi. Dari kecil ia sudah terbiasa mendengar gamelan dan tembang Jawa, lalu jatuh hati pada peran sinden yang menghubungkan penari, pemusik, dan penonton. Kadang ia harus spontan menyesuaikan syair dengan gerakan penari, atau memberi tanda pada pemusik ketika suasana mencapai puncak.
“Kalau penari sudah kesurupan, sinden dan pemusik harus pintar-pintar mengendalikan suasana. Jangan sampai penonton takut, tapi tetap merasa terhibur” tambahnya.
Gerakan Gagah, Jiwa yang Menyatu.
Tak jauh dari Mbak Sum, seorang pemuda bernama Sendi duduk di pinggir jalan, masih berkeringat setelah selesai menari. Kuda anyaman bambu yang tadi ia tunggangi tergeletak di sampingnya. Nafasnya terengah, tapi matanya berbinar.
“Ebeg itu bukan hanya menari. Rasanya seperti menyatu dengan irama kendang dan kuda,” katanya pelan.
Sendi sudah bergabung dengan kelompok ebeg sejak remaja. Ia belajar gerakan dasar sendiri, lalu jatuh cinta pada sensasi bebas yang ia rasakan di panggung. Menurutnya, ebeg memberi ruang untuk mengekspresikan diri: gerakan gagah, meloncat, menghentak tanah, hingga tubuh seakan dikuasai energi tak kasat mata.
“Kadang orang bilang seram karena ada yang kesurupan. Tapi buat kami, itu bagian dari pertunjukan. Justru di situlah penonton merasa kagum,” jelasnya.
Jalanan Jadi Panggung Rakyat
Yang unik di Pemalang, terutama beberapa tahun terakhir adalah lokasi pentas yang sering bergeser dari lapangan desa ke ruas jalan utama. Alasannya sederhana, lebih mudah mengumpulkan penonton. Jalan yang ramai otomatis jadi pusat perhatian, dan warga desa seolah tak keberatan untuk menutup akses sementara demi menyambut kesenian mereka.
Begitu musik dimulai, toko-toko menutup pintu sebentar, anak-anak duduk di trotoar, pedagang asongan berkeliling menawarkan kacang rebus dan es teh. Jalan berubah menjadi ruang budaya, batas antara pemain dan penonton seolah lenyap.
“Kalau di jalan, lebih ramai. Orang lewat bisa berhenti sebentar untuk nonton, lalu ikut larut dalam suasana. Itu yang membuat ebeg terasa hidup,” tutur Sendi.
Antara Hiburan dan Tradisi.
Ebeg memang identik dengan trance atau kondisi tak sadar, yang sering membuat penonton tercengang. Penari bisa memakan pecahan kaca, atau melakukan gerakan di luar nalar. Namun, bagi warga Desa Jojogan, hal itu bukan sekadar pertunjukan ekstrem. Ia dianggap bagian dari warisan spiritual Jawa yang menghubungkan manusia dengan kekuatan leluhur.
“Yang penting penonton merasa terhibur dan tidak ada yang celaka.” jelas Mbak Sum sambil merapikan selendangnya.
Meski begitu, ebeg juga beradaptasi. Kini beberapa kelompok mulai menggabungkan irama modern, menambahkan alat musik elektronik, bahkan memperpendek durasi pertunjukan agar sesuai dengan selera penonton zaman sekarang.
“Anak muda sekarang kan maunya serba cepat. Kalau durasi terlalu lama, mereka bosan. Jadi kami sesuaikan, tapi tetap tidak meninggalkan pakem tradisi,” kata Sendi.
Magnet Kebersamaan
Lebih dari sekadar tarian, ebeg adalah perekat sosial. Di setiap pementasan, warga desa berkumpul tanpa memandang status sosial. Ada yang pedagang, petani, hingga anak sekolah. semua duduk bersama di pinggir jalan, menikmati pertunjukan yang sama.
Di sela-sela musik, orang tua mengobrol tentang sawah atau harga gabah, remaja saling bercanda, anak kecil tertawa ketika penari membuat gerakan lucu. Sesekali, sinden melempar pantun atau syair spontan yang membuat penonton riuh ramai.
“Kalau tidak ada ebeg, desa terasa sepi. Dengan ebeg, orang bisa ketemu, ngobrol, tertawa bareng. Itulah yang membuat kami selalu menunggu-nunggu pertunjukan,” ucap Mbak Sum dengan mata berbinar.
Bertahan di Tengah Arus Modernitas
Pertanyaan pun muncul, mengapa ebeg tetap bertahan, bahkan ketika hiburan modern sudah begitu mudah diakses lewat gawai? Jawabannya terletak pada nilai yang ia bawa. Ebeg bukan sekadar tontonan, ia adalah pengalaman kolektif, sesuatu yang tidak bisa digantikan layar kaca.
“Di sini, orang bisa merasakan getarannya langsung. Suara gamelan, teriakan penonton, debu jalanan yang naik ketika penari menghentak kaki. Disitulah letak serunya.” ujar Sendi.
Meski demikian, tantangan tetap ada. Generasi muda tidak semuanya tertarik. Sebagian memilih musik modern atau hiburan digital. Namun, keberadaan orang-orang seperti Mbak Sum dan Sendi membuktikan bahwa masih ada yang rela melanjutkan estafet tradisi.
“Kalau bukan kita yang muda, siapa lagi? Ebeg itu bagian dari darah Pemalang,” tutup Sendi dengan senyum penuh keyakinan.
Jejak Irama yang Tak Pernah Padam
Malam semakin larut, namun suara gamelan masih menggema di jalan desa. Penonton belum beranjak, meski udara makin dingin. Beberapa penari sudah jatuh dalam kondisi trance atau biasa dikenal dengan istilah kesurupan maupun kerasukan. ditenangkan perlahan oleh pawang. Sementara itu, Mbak Sum masih melantunkan tembang dengan suara yang stabil, seakan memberi penutup pada cerita hari itu.
Pertunjukan mungkin akan selesai, penonton akan pulang, dan jalan kembali dipenuhi kendaraan. Namun, esensi ebeg tetap hidup, ia menjadi penanda bahwa tradisi tidak pernah benar-benar hilang, melainkan terus mencari ruang baru untuk bernafas.
Ebeg bukan sekadar kesenian, melainkan jejak budaya yang terus berdentum di denyut nadi Desa Jojogan, Pemalang, Jawa Tengah.