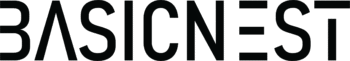Rumah masa kecilku punya lahan terbuka, lebih lebar dari luas bangunan yang hanya sepetak. Kamu bisa menemukan kebun kopi berbiji Gunung Halu, persis di pekarangan belakang, di antara barisan pohon lengkeng dan jambu batu. Sepetak tanah yang tak lebih luas dari halaman parkir itu, ditumbuhi beberapa batang kopi, yang entah bagaimana bisa bertahan hidup di tanah Bandung yang kian padat oleh bangunan dan aspal. Ya, tempat tinggalku bukan kawasan perkebunan. Ia bukan Pangalengan, bukan Ciwidey, bukan dataran tinggi yang sering disebut-sebut dalam peta wisata kopi. Ia hanyalah pinggiran kota yang setengah urban, setengah desa, tempat di mana sawah sudah menyusut, rumah kontrakan tumbuh menjamur, dan suara ayam tetap ada bersahutan dengan deru kendaraan bermotor. Namanya kawasan Caringin, di Bandung bagian Selatan.
Di kawasan rural pinggiran kota Bandung ini, Ema Nini mengajarkanku sesuatu: tradisi sangrai kopi. Ema Nini bukan seorang barista kedai kopi bergaya industrial. Ia cuma seorang perempuan lanjut usia, yang meski tangannya berkerinyut urat tua tapi tetap sigap mengolah biji kopi, dengan sorot matanya yang menyimpan kesabaran. Ema Nini, tak pernah menyebut kopi sebagai “single origin” atau “arabika robusta blend”. Baginya, kopi ya kopi. Biji hitam yang harus diperlakukan dengan hormat, dipetik dengan doa, dijemur dengan sabar, dan disangrai dengan penuh perhatian.
Di dunia urban-ku yang tergesa-gesa, tradisi sangrai kopi tampak asing karena warga sini terbiasa membeli kopi sachet-an. Dan justru dari situlah selain rumah kami harum karena sangrai kopi, nama Ema Nini juga jadi dikenal oleh banyak orang. Sangrai kata Ema Nini, bukan sekadar teknik. Ia adalah sebuah mini-ritual. Biji kopi yang sudah kering dituang ke dalam wajan tanah liat, lalu diaduk pelan di atas bara api. Bau tutung perlahan naik, berganduh di udara, menyusup ke celah-celah dinding rumah. Tangannya bergerak lambat, tapi mantap, seolah ia tahu kalau setiap putaran proses mengaduk adalah bagian dari ritual berdoa.
“Lamun sabar, tangtu gumelar,” katanya suatu kali. Kalau sabar, tentu muncul dengan benar. Maksudnya, kopi bisa saja gosong bila diolah dengan terburu-buru. Tapi aku menangkap lebih dari itu. Ia sedang mengajariku tentang hidup, lewat biji kopi yang meliuk di atas wajan dan api, dikelola dengan kesabaran.
Tradisi sangrai kopi ini, bila dilihat dari kacamata modern, barangkali terlalu sederhana. Tapi justru kesederhanaan itu kini malah sulit dicari. Di zaman mesin roasting industri, aroma kopi pabrikan, lalu dibungkus dalam kantong aluminium, dan dilabeli dengan nama daerah yang eksotis. Mungkin kita lupa, kalau dulu, kopi bukan sekadar komoditas. Ia adalah peristiwa rumah tangga, bagian dari irama rutinitas sehari-hari.
Aku masih ingat ketika masih jadi bocah perempuan kecil, barangkali terlalu cilik untuk dikenalkan pada rasa pahit. Tapi justru dari situlah aku belajar. Ema Nini yang pertama kali mengajarkan aku cara menikmati kopi tubruk, di dalam cangkir kecil yang sengaja ia balik menghadap piring kecil, lalu menyeruputnya. Tanpa gula, tanpa susu, tanpa tambahan sirup-sirup warna-warni seperti warung kopi skena hari ini. Hanya kopi hitam pekat. Kadang saat siang terik, ia menambahkan sebongkah es. Aku menyeruputnya, mencoba menahan getir yang menempel di lidah.
Dari situ aku paham, mencintai kopi berarti menerima rasa pahit. Dan Ema Nini mengajariku mencintai kopi dengan cara yang paling jujur: tidak ditutup-tutupi rasa aslinya, tidak dipoles, tidak didekorasi dengan beraneka perasa.
Bandung, kota yang kini dijejali dengan kedai kopi bergaya minimalis, yang mengkomodifikasi kopi sebagai gaya hidup. Kita bertemu di kafe, memotret cangkir, menandai lokasi, dan memberi tanda suka di layar media sosial. Tapi di belakang rumahku, di tangan Ema Nini, kopi justru hadir sebagai bagian dari menyimpan ingatan. Ia mengingatkan aku pada sebuah dunia yang berjalan pelan, dunia yang mau mendengar celoteh burung tekukur dan dersik angin menyentuh daun mengkudu. Dunia yang tidak keberatan menunggu biji berubah warna dari coklat muda, menjadi hitam mengilap.
Aku sering berpikir, mungkin kopi—dalam tradisi sangrai—lebih dekat kepada “waktu”. Ia tak bisa disegerakan. Ia menuntut orang duduk, mengaduk, menunggu. Sama seperti cara hidup yang sekarang jarang kita temui. Dalam sangrai kopi, kita dipaksa kembali ke kesadaran paling sederhana, bahwa sesuatu itu butuh proses.
Ema Nini tidak paham apa itu filsafat. Ia tidak menyitir kata-kata besar ala filsuf stoicism. Tapi lewat caranya menggunakan wajan dari tanah liat, aku tahu ia sedang mengajariku cara berdamai dengan kenyataan hari ini.
Ketika kopi sudah selesai disangrai, biji itu ditumbuk dengan alu kayu. Suara ketukan bergema, mengalun ritmis, seolah ada musik purba yang menyatukan manusia dengan tanah. Kopi yang sudah hancur lalu diseduh dalam teko sederhana, bukan dengan mesin pres mahal yang berkilat. Air panas dituang, bubuk kopi melayang-layang, perlahan turun sampai residunya mengendap. Tak ada penyaring kertas, tak ada latte art. Hanya cairan hitam pekat, dengan aroma yang menenangkan.
Kopi Gunung Halu ala Ema Nini, bila diminum terasa pahit. “Hirup mah kudu wani, kawas nginum kopi,”katanya. Hidup harus berani, seperti minum kopi. Aku sering merenung: mengapa tradisi kecil ini terasa begitu penting? Mungkin karena ia mengikatku pada akar. Di tengah arus urban, ketika rumah-rumah dibangun semakin rapat, ketika pohon ditebang demi lahan parkir, ketika mall menggantikan lapangan bermain, sepetak kebun kopi di belakang rumah menjadi semacam perlawanan.
Sangrai kopi bukan sekadar mengglorifikasi sebuah romantika, Ia adalah bukti bahwa kearifan lokal bisa tetap hidup, bahkan di tempat yang tidak lagi terasa seperti kampung halaman. Ia terlalu kecil, terlalu domestik, tapi justru di situlah kekuatannya. Ia hadir di halaman belakang, dari tangan seorang nenek tua yang sabar, dan di lidah seorang bocah perempuan yang belajar mencintai pahit sejak dini. Lalu mungkin, pada akhirnya kopi itu bukan cuma minuman. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations: “You have power over your mind—not outside events. Realize this, and you will find strength.”
Kopi pahit di cangkir kecilku adalah pengingat paling sederhana dari kalimat itu. Kita tidak bisa mengendalikan dunia yang tergesa-gesa, urbanisasi yang merampas sebuah ruang, atau modernitas yang serba buru-buru. Tapi kita bisa memilih menyambutnya dengan tenang dan berani, dengan secangkir kopi hitam yang diajarkan Ema Nini untuk kucintai meski lewat pahit.
Caringin pinggiran, tempat aku tinggal, adalah ruang perbatasan. Ia bukan lagi desa, tapi juga belum sepenuhnya kota. Tradisi sangrai kopi Ema Nini mungkin tidak akan masuk buku sejarah.
Ketika aku menulis catatan ini, aku teringat lagi bau hangit itu. Bau yang tidak bisa ditemui di kedai kopi bergaya modern. Bau yang bercampur dengan suara ayam, suara anak-anak berlari di gang, dan suara motor tua lewat. Bau yang membawa aku pada sesuatu yang lebih dalam: kesadaran bahwa hidup, betapapun berubah, masih menyisakan ruang untuk kesederhanaan.