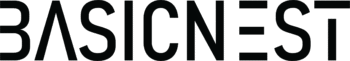Udara malam itu terasa berbeda. Dinginnya tidak menusuk, tapi justru menenangkan, seakan ikut mendampingi langkah warga desa yang satu per satu berdatangan menuju perempatan besar di jantung kampung. Di sana, jalan-jalan kecil bertemu, menjelma titik sakral yang sejak lama menjadi tempat berkumpul setiap malam 1 Suro. Lampu-lampu jalan yang redup menyorot wajah-wajah penuh harap, sementara terpal dan tikar digelar sebagai alas kebersamaan.
Di tangan warga, terbungkus rapi nasi berkat yang sejak sore sudah disiapkan di rumah nasi putih hangat dengan lauk sederhana, simbol syukur yang akan segera berpadu dengan milik tetangga lain. Perlahan, tumpukan ambengan itu membentuk gunungan kecil di tengah perempatan, menunggu doa yang akan mempersatukan semuanya.
Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah bercampur wangi masakan. Suara obrolan kecil warga menyatu dengan lantunan doa yang mulai dipanjatkan, menimbulkan suasana syahdu yang membuat bulu kuduk meremang. Ada rasa yang sulit dilukiskan: keheningan yang tidak sepi, kebersamaan yang tidak ramai, dan ketulusan yang tak pernah lekang oleh zaman.
Di malam 1 Suro itu, semua orang seakan menjadi satu keluarga besar. Tidak ada sekat, tidak ada perbedaan. Hanya doa yang bergema, nasi yang dikumpulkan, dan kebersamaan yang menghangatkan di bawah langit gelap berhias bintang.
Apa yang terjadi di perempatan besar malam itu bukan sekadar keramaian musiman. Bagi warga Kediri, khususnya di desa-desa, momen 1 Suro identik dengan tradisi bersih desa. Inilah cara mereka merawat harmoni: berdoa bersama, berbagi makanan, dan memohon keselamatan untuk seluruh kampung.
Setiap keluarga diwajibkan membawa nasi berkat atau ambengan dari rumah. Lauknya bisa berbeda ada yang membawa ayam goreng, ikan, urap, atau sekadar tempe orek tetapi semuanya diletakkan di satu titik yang sama, lalu dikumpulkan menjadi tumpukan penuh syukur. Setelah doa bersama dipanjatkan, nasi itu dibagikan kembali kepada siapa pun yang hadir. Tidak peduli siapa yang membawa sedikit atau banyak, semua orang berhak mendapatkan bagian.
Lokasi perempatan dipilih bukan tanpa alasan. Ia adalah simpul desa, tempat jalan bertemu, simbol persimpangan kehidupan. Berkumpul di sana menghadirkan rasa kebersamaan yang nyata, jalan desa seolah berhenti sejenak dari lalu lalang kendaraan, memberi ruang bagi doa, lantunan ceramah, dan tawa ringan warga yang duduk bersisian.
Tradisi ini memang sederhana. Tidak ada panggung megah, tidak ada tata lampu gemerlap. Tetapi justru di kesederhanaan itulah letak kekuatan, sebuah ritual kolektif yang menyatukan hati dan meneguhkan rasa syukur, tahun demi tahun tanpa pernah lekang.
Dari luar, tradisi bersih desa 1 Suro mungkin terlihat sebagai acara makan bersama yang sederhana. Namun di balik setiap piring berkat yang berpindah tangan, tersimpan makna yang dalam.
Gotong royong adalah jiwa utamanya. Ketika nasi dan lauk dari setiap rumah dikumpulkan jadi satu, tidak ada lagi identitas “punya siapa”. Semuanya bercampur, melebur dalam doa bersama, lalu dibagikan kembali dengan adil. Simbol bahwa rezeki, sebesar atau sekecil apa pun, adalah titipan yang seharusnya bisa menguatkan banyak orang.
Tradisi ini juga menjadi cara warga desa merawat rasa syukur. Dengan duduk bersila di jalanan beralas tikar, tanpa pembeda antara kaya atau miskin, semua orang diingatkan bahwa hidup bukan soal siapa yang memiliki lebih banyak, melainkan siapa yang bersedia berbagi.
Lebih jauh, berkumpul di perempatan besar bukan hanya soal tempat yang strategis. Ia adalah titik temu, sebuah metafora bahwa hidup selalu berada di persimpangan, penuh pilihan dan arah. Dengan berdoa bersama di sana, warga seakan menyepakati satu hal, apa pun jalan yang ditempuh, keselamatan dan kebersamaan desa adalah tujuan utama.
Dalam heningnya doa dan hangatnya kebersamaan, tradisi ini menjadi penegas bahwa spiritualitas dan sosialitas berjalan beriringan. Kesederhanaan nasi berkat bukan sekadar makanan, melainkan bahasa persaudaraan yang universal.
Ada momen yang selalu membekas di ingatan setiap kali mengikuti bersih desa 1 Suro. Saat doa mulai dilantunkan, suasana seketika berubah hening. Hanya terdengar suara imam yang bergetar, berpadu dengan bisikan angin malam yang lewat pelan di sela pepohonan. Udara dingin merayap ke kulit, tapi hangatnya kebersamaan membuat tubuh tak gentar.
Di hadapan, gunungan nasi berkat yang sebelumnya menumpuk perlahan dibagikan. Sepiring nasi yang sampai di tangan terasa berbeda bukan hanya soal rasa lauk sederhana, tetapi rasa haru karena tahu itu adalah hasil dari kebersamaan seluruh warga. Menyantapnya di tikar bersebelahan dengan tetangga, sambil tertawa kecil dan berbagi lauk tambahan, menghadirkan sensasi yang tidak bisa dibeli dengan apa pun.
Ada juga momen setelah acara usai. Sebagian warga memilih membawa pulang sisa berkat ke rumah. Rasanya unik, karena makanan yang dibawa pulang bukan sekadar nasi, melainkan berkah yang diyakini membawa keselamatan dan rezeki. Bahkan ketika disantap di rumah keesokan harinya, masih ada rasa syahdu yang tersisavseperti sepotong doa yang ikut termakan bersama nasi hangat itu.
Malam 1 Suro selalu meninggalkan getar dalam hati, perasaan kecil di hadapan semesta, sekaligus rasa besar karena menjadi bagian dari kebersamaan yang begitu indah. Di sanalah saya merasakan bahwa tradisi bukan hanya warisan, melainkan pengalaman spiritual yang hidup di dalam diri.
Di tengah hiruk pikuk zaman yang semakin modern, tradisi seperti bersih desa 1 Suro sering dianggap kuno, atau sekadar ritual tahunan tanpa makna. Namun, jika dicermati, justru di sinilah letak relevansinya.
Kehidupan modern perlahan mendorong manusia pada individualisme. Kesibukan kerja, layar gawai, hingga ritme kota membuat orang kerap lupa menyapa tetangga di sebelah rumah. Tradisi bersih desa hadir sebagai penawar ruang di mana semua orang kembali duduk bersama, saling menatap, saling mendengar, dan berbagi makanan dari piring yang sama.
Nilai spiritualnya pun tak kalah penting. Di era yang penuh ketidakpastian dari ekonomi, kesehatan, hingga bencana alam doa kolektif yang dipanjatkan di malam Suro menjadi simbol keteguhan. Bukan sekadar permintaan pada Tuhan, tetapi juga pengingat bahwa manusia tak bisa hidup sendiri. Ada kekuatan besar dalam doa bersama, dalam energi kolektif yang menyatukan harapan seluruh warga.
Bagi generasi muda, tradisi ini bisa menjadi cermin. Bahwa kemajuan teknologi tidak seharusnya memutus tali sosial, melainkan bisa berdampingan dengan kearifan lokal. Bersih desa bukan hanya cerita lama, tetapi warisan yang mengajarkan cara sederhana untuk merayakan syukur dan kebersamaan.
Justru ketika dunia semakin cepat dan individualistis, ritual yang tenang, syahdu, dan penuh kebersamaan ini terasa semakin penting untuk dilestarikan. Ia bukan hanya tentang masa lalu, melainkan tentang masa depan: bagaimana masyarakat tetap bisa menjaga rasa, meski zaman terus berubah.
Tradisi bersih desa 1 Suro di Kediri mungkin tak pernah tersorot kamera televisi, tidak ramai jadi bahan liputan nasional, dan tidak pula diselimuti gemerlap pesta. Namun justru di situlah keistimewaannya. Ia hidup sederhana, diam-diam, namun terus bertahan di hati warga yang menjalaninya.
Dari sepiring nasi berkat, kita belajar tentang berbagi. Dari doa bersama di perempatan, kita belajar tentang kebersamaan. Dari dinginnya angin malam, kita belajar tentang kehangatan yang lahir dari kebersamaan hati.
Inilah cerita membanggakan yang jarang terlihat di layar kaca, kisah tentang masyarakat yang memilih syukur daripada keluh, memilih berbagi daripada menyimpan sendiri, dan memilih bersama-sama daripada berjalan sendirian.
Malam 1 Suro akan terus datang setiap tahun. Dan semoga, bersama semilir angin dan cahaya redup di perempatan desa, doa-doa itu selalu menemukan jalannya, menjaga keselamatan, menguatkan kebersamaan, dan mewariskan syahdu yang tak lekang oleh waktu.